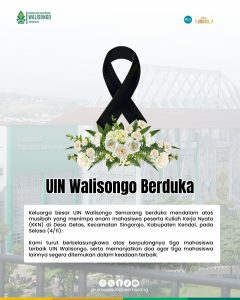oleh Eko Widianto—Dosen UIN Walisongo Semarang & Mahasiswa PhD di University of Galway, Ireland
Presiden Prabowo baru saja memunculkan pernyataan yang mengundang perbincangan publik. Gagasannya untuk memasukkan bahasa Portugis menjadi mata pelajaran di sekolah menuai banyak komentar baik positif maupun negatif. Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Brasil dalam pertemuan bilateral yang terjadi di Istana Merdeka baru-baru ini.
Sebagai seorang kepala negara, pernyataan itu menjadi wacana yang tidak netral. Sebagian kalangan menilai ini hanya wujud komunikasi diplomatik saja. Terlebih, Presiden Prabowo memang dikenal memiliki pola komunikasi yang spontan dan strategis. Tidak heran rasanya jika pernyataan tersebut dinilai tidak lebih dari sekadar ‘lip service’. Namun, bagaimana jika wacana ini benar-benar diimplementasikan?
Menilik esensi dan urgensi bahasa Portugis di Indonesia tampaknya tidak adil tanpa melihat bagaimana kedudukan bahasa ini di kancah global. Menjadi salah satu dari 10 bahasa resmi yang diakui dan digunakan dalam sidang umum UNESCO, bahasa Portugis memiliki jumlah penutur sekitar 280 juta jiwa. Bahasa ini juga dituturkan secara luas di negara komunitas penutur bahasa Portugis selain Portugal (CPLP) seperti Brasil, Angola, Mozambik, dan sebagainya. Artinya, kedudukannya cukup strategis dan diperhitungkan dalam panggung internasional.
Namun, amat naif rasanya jika keputusan fundamental seperti memasukkan bahasa asing ke dalam kurikulum nasional hanya dengan pertimbangan instan seperti itu. Terlebih, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Portugal juga tidak terlalu kuat kuat. Bahkan, keduanya sempat ‘putus-nyambung’ di tengah dinamika geopolitik Indonesia—Timor Timur (kini Timor Leste). Begitu pula dengan Brasil, skala kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Brasil dapat dikatakan tidak lebih besar dari negara-negara lain seperti AS, Australia, UK, atau RRT. Lalu, mengapa bahasa Portugis perlu masuk ke dalam kerangka kurikulum nasional kita?
Padahal, bangsa Indonesia tengah dihadapkan persoalan kebahasaan yang amat mendasar. Kita dikenal sebagai bangsa yang multilingual. Setiap anak terlahir dwibahasa, setidaknya bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Setelah tumbuh, mereka akan belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing di sekolah. Sayangnya, English First mencatat bahwa English Proficiency Index bangsa Indonesia sangat rendah, yakni di peringkat 80 dari 116 negara. Tren ini juga cenderung turun dari tahun ke tahun. Di level ASEAN, kita masih kalah dari Singapura, Malaysia, Filipina, bahkan Vietnam. Di saat bangsa Indonesia masih ‘belepotan’ mengelola pembelajaran salah satu bahasa asing, apakah kehadiran bahasa Portugis menjadi solusi? Atau, justru akan menambah daftar tantangan baru untuk kondisi kebahasaan kita?
Dari perspektif regional, kita juga dihadapkan dengan kondisi sosiolinguistik yang amat kompleks. Badan Bahasa merilis jumlah bahasa daerah yang berhasil dikodifikasi. Terdapat setidaknya 718+ bahasa daerah, tetapi dengan beragam status vitalitas. Dari sekian banyak bahasa daerah ini, hanya 18 bahasa dengan status aman. Selebihnya berstatus rentan, kritis, hingga terancam punah. Pemertahanan dan revitalisasi bahasa daerah menjadi isu penting yang lebih layak diperbincangkan. Alih-alih membicarakan relevansi bahasa asing ke dalam kurikulum, fokus terhadap konservasi bahasa daerah sejatinya lebih esensial untuk memenuhi ruang diskusi kita hari ini. Apalagi, fakta menunjukkan bahwa salah satu faktor pergeseran dan kepunahan bahasa daerah disebabkan oleh dominasi bahasa nasional dan bahasa asing.
Dari segi kebijakan bahasa, kita juga tengah disibukkan dengan implementasi penginternasionalan bahasa Indonesia yang diamanatkan UU Nomor 24 Tahun 2009. Badan Bahasa rajin mengirimkan guru-guru bahasa Indonesia ke luar negeri. Pelbagai bahan diplomasi juga secara reguler diproduksi dan didistribusikan. Bahkan, pada tahun 2023 bahasa Indonesia telah mendapatkan rekognisi nyata sebagai bahasa yang diakui dalam sidang umum UNESCO. Tahun 2025 menjadi tahun pertama bahasa ini digunakan di sidang umum tersebut. Namun, tanggung jawab ini tidak semestinya hanya dibebankan pada satu dua lembaga seperti Badan Bahasa saja. Ini semestinya “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.
Bulan Oktober menjadi momentum peringatan bulan bahasa. Ironisnya, melalui wacana pengajaran bahasa Portugis, Presiden Prabowo justru secara tidak langsung sedang mendiskreditkan bahasa Indonesia di rumah sendiri. Dalam perayaan bulan bahasa ini, seharusnya presiden mengambil kesempatan untuk memartabatkan bahasa Indonesia di panggung global. Di mimbar istimewa tersebut, semestinya presiden lantang menunjukkan kedaulatan bahasa kita. Sepercaya diri dan sekharismatik saat menyampaikan pidato di podium PBB, seperti itulah yang selayaknya kita saksikan ketika presiden kita memartabatkan bahasa Indonesia kepada mitra internasional.
Namun, angan hanyalah angan—cita hanyalah cita. Bahasa tidak pernah menjadi isu strategis. Kedudukannya hanya menjadi arena ideologis. Kita tidak pernah mendengar presiden membincangkan secara serius kondisi bahasa Indonesia dan bahasa daerah, karena mungkin bahasa kita tidak seserius itu. Kita tidak pernah benar-benar berdaulat secara bahasa. Kita bisa bertasbih menjadi negara yang merdeka. Tapi kedaulatan bahasa kita, layak dipertanyakan; sejak dalam pikiran!